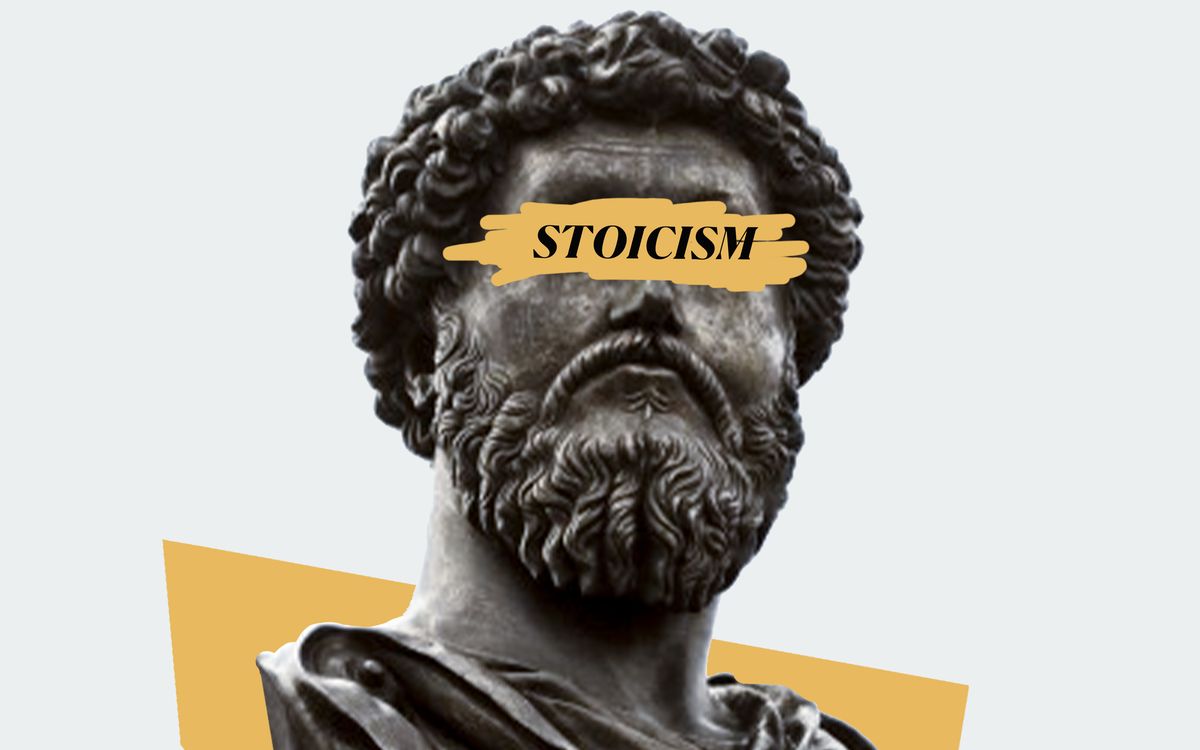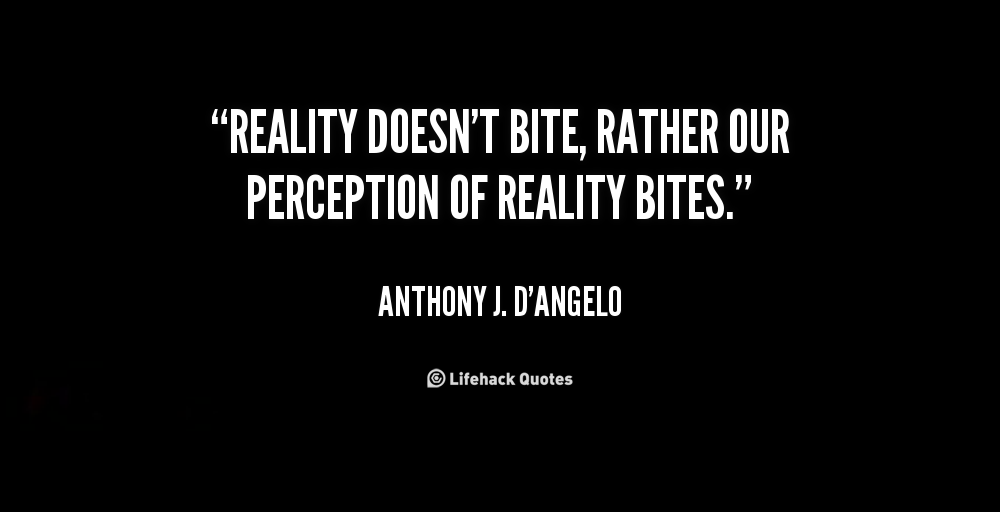"When casting your vote, remember that the true measure of a leader lies not in their rhetoric, but in their adherence to the principles of justice and virtue." — Epictetus
Menjelang pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024 mendatang, saya tergelitik menulis sesuatu berdasarkan prinsip filsafat praktis Stoikisme yang saya pahami sejauh ini.
Filsafat Stoikisme adalah filsafat praktis yang mengajarkan laku hidup selaras dengan alam, dan salah satu bentuk nyatanya adalah menjadi warga negara yang baik. Seperti apakah kiranya warga negara yang baik itu? Dalam konteks pemilihan umum, menjadi warga negara yang baik tidak hanya berhenti pada persoalan menggunakan hak pilih (voting rights) yang dijamin dalam undang-undang, tetapi lebih dari itu, juga mempertimbangkan dengan matang dan berkomitmen memilih pemimpin yang menghidupi keutamaan-keutamaan (virtues) demi kemaslahatan orang banyak. Memilih pemimpin yang pantas dan baik adalah juga tanggungjawab moral warga negara.

Mari kita eksplorasi prinsip-prinsip Stoikisme yang kiranya bisa diaplikasikan dalam memilih pemimpin bangsa.
1. Kebajikan sebagai kriteria utama: Stoikisme mengajarkan kita untuk memprioritaskan kebajikan (virtues) di atas segalanya. Ketika mengevaluasi calon pemimpin potensial, pertimbangkanlah dengan baik karakternya, integritasnya, dan komitmennya pada prinsip-prinsip etika. Jangan hanya berhenti pada hal-hal yang tampak dari luar saja, tetapi lihatlah pula bagaimana kebijaksanaannya, bagaimana ia berlaku adil, keberaniannya, dan kemampuannya untuk mengendalikan diri. Keempat kebajikan ini (wisdom, courage, justice, temperance) adalah keutamaan-keutamaan yang sangat dijunjung tinggi dalam Stoikisme, dan rasa-rasanya kalau nilai-nilai ini bisa diejawantahkan dalam bentuk perilaku, maka orang yang menghidupinya tentu sangat pantas dijadikan sebagai pemimpin. Pilihlah pemimpin yang ‘menampakkan’ nilai-nilai ini secara konsisten, karena akan besar kemungkinan bahwa mereka akan memikirkan kepentingan orang banyak dan akan membuat keputusan-keputusan yang memihak rakyat.
2. Berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan: Di tengah retorika politik dan janji-janji kampanye, sangat mudah untuk ‘hanyut’ dalam faktor-faktor eksternal yang di luar kendali kita. Stoikisme sebagai filsafat praktis mengingatkan kita untuk tetap berfokus pada apa yang ada dalam kendali kita: pikiran, tindakan, dan pilihan-pilihan sikap yang kita ambil. Ketimbang ‘tenggelam’ dalam berbagai ketidakpastian dalam lanskap perpolitikan, kita bisa mengerahkan energi untuk meriset kandidat, memahami cara berpikir mereka, dan secara kritis menganalisis kebijakan-kebijakan yang akan mereka luncurkan jika nantinya terpilih.
3. Praktikkan mempertimbangkan dengan cermat: Stoikisme sangat menekankan kita untuk senantiasa melatih diri membuat pertimbangan-pertimbangan cermat dalam semua aspek kehidupan. Ketika mengevaluasi kandidat, hindari membuat keputusan yang hanya berdasarkan emosi, bias, atau tekanan dari luar. Ambil waktu untuk mengumpulkan informasi, melihat bukti-bukti yang ada, dan menetapkan konsekuensi yang mungkin terjadi dari apa yang kita pilih (seperti layaknya praktik premeditatio malorum). Ingatlah bahwa tujuannya bukan untuk mendukung calon yang sempurna, tetapi memilih individu yang kiranya sejalan dengan nilai-nilai ideal Stoikisme dan yang berpotensi paling besar untuk memimpin dengan bijaksana dan berintegritas.
4. Terima hasil akhirnya: Dalam Stoikisme, menerima hal-hal eksternal adalah prinsip kunci. Ini dikenal dengan amor fati. Apa pun kiranya hasil pemilihan umum nantinya, berjuanglah untuk tetap menjaga ketenangan dan sikap ksatria. Pahamilah bahwa Anda telah menjalankan bagianmu sebagai seorang warga negara yang bertanggungjawab, dan hasil akhirnya berada di luar kendali kita. Apabila calon yang kita pilih ternyata tidak menang, berfokuslah pada kontribusi positif yang bisa kita sumbangkan untuk masyarakat, dimulai dari lingkaran terkecil kita, sembari tetap memegang teguh prinsip-prinsip Stoikisme yang kita yakini. Para guru Stoik juga mengajarkan bahwa situasi yang tidak sesuai harapan sekalipun bisa menjadi arena untuk belajar nilai-nilai dan bertumbuh. Pun kalau kandidat yang kita dukung menang, kita tidak lantas berdiam diri setelah pemilihan usai. Kita harus terlibat dalam menjaga orang-orang yang terpilih tetap akuntabel, dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip keutamaan yang 4 tadi.

Intinya, menerapkan prinsip-prinsip Stoikisme dalam memilih pemimpin dalam pemilihan umum bisa membantu kita menjadi warga negara yang lebih bertanggungjawab. Menjalankan peranan sebagai warga negara secara bertanggungjawab juga akan membantu menciptakan tatanan masyarakat yang lebih baik ke depannya. Setiap warga negara memiliki daya untuk menentukan masa depan bangsanya. Maka mari memilih dengan bijak, dan semoga sedikit uraian prinsip Stoik ini membantumu menjadi warga negara yang baik, yang terlibat aktif, yang bertanggungjawab secara moral. Pada akhirnya, semua untuk kebaikan bangsa. ☺️